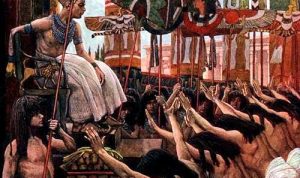Penulis: Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
Mabesnews.com,-Keputusan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keppres No. 122/P Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian dengan memasukkan nama Listyo Sigit Prabowo, kembali menempatkan publik pada situasi yang sejak lama menyesakkan, dimana jarak antara harapan rakyat dan logika kekuasaan terasa begitu lebar. Di tengah tuntutan luas untuk mengakhiri polemik yang menyelimuti kepemimpinan Sigit sebagai Kapolri, ia justru diberikan posisi sebagai pengarah reformasi institusi yang selama ini dikritik karena carut-marut di era yang sama. Dalam tradisi filsafat akal sehat, common sense yang kerap disebut sebagai prinsip penilaian paling universal, keputusan ini terasa sulit dipahami.
Kekecewaan itu tidak berhenti sebagai bisik-bisik publik. Ia pecah terang menjadi peristiwa simbolik ketika sejumlah tokoh masyarakat memilih walk out dari ruang audiensi Komisi Reformasi Polri.
Kehadiran Roy Suryo dan rekan-rekannya ditolak karena status tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, sebuah perkara yang banyak kalangan menilai mengandung motif politik.
Penjelasan Jimly Asshiddiqie bahwa komisi tidak elok mendengar pandangan seorang tersangka justru menimbulkan pertanyaan baru. Jimly sebelumnya menyatakan kasus tersebut bahkan tidak layak dibawa ke pengadilan, tetapi pada saat bersamaan menolak kehadiran tokoh yang ia nilai tidak layak diadili. Di sinilah retakan nalar itu semakin tampak, dimana argumentasi yang dibangun di ruang akademik runtuh di hadapan dinamika kekuasaan.
Penolakan tersebut sekaligus memperlihatkan kegamangan komisi dalam mendefinisikan dirinya. Bila komisi reformasi tidak boleh mendengarkan persoalan-persoalan yang mengemuka dalam kasus-kasus aktual Polri, lalu dari mana reformasi itu akan dimulai?
Secara teoritis, sebagaimana diulas dalam kajian David Bayley dan Andrew Goldsmith mengenai reformasi kepolisian, suara warga yang terdampak langsung adalah sumber informasi paling otentik bagi perombakan institusi.
Reformasi justru berangkat dari keberanian menyingkap patologi internal yang tercermin dalam kasus-kasus kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan, atau ketidakseimbangan hubungan sipil-polisi. Menolak suara-suara itu hanya menegaskan bahwa komisi lebih sibuk menjaga kenyamanan elit ketimbang membongkar akar persoalan.
Fenomena inilah yang mencuatkan istilah Listyo Syndrome, sebuah kondisi ketika mereka yang diberi mandat mengawasi justru terserap dalam orbit kekuasaan yang seharusnya mereka koreksi. Dalam psikologi politik, keadaan ini dikenal sebagai institutional capture, yakni saat figur independen mulai meminjam kacamata lembaga yang sedang bermasalah.
Perlahan, sikap kritis berubah menjadi rasionalisasi, jarak objektif menyempit, dan seorang pengarah reformasi tanpa disadari berubah menjadi pembela status quo. Dalam konteks ini, kemunculan Sigit di komisi bukan sekadar soal nama, tetapi cermin dari bagaimana kekuasaan membangun lingkaran yang sulit ditembus oleh akal sehat.
Listyo Sigit memang telah lama memunculkan perdebatan publik. Banyak kasus besar di era kepemimpinannya berakhir menjadi noda dalam catatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Namun tetap bertahannya ia dalam posisi strategis, bahkan kini sebagai bagian dari komisi reformasi, menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan lagi soal kinerja personal, tetapi kultur politik yang menganggap reformasi sebagai serangkaian keputusan administratif belaka. Reformasi Polri membutuhkan keberanian moral, bukan sekadar daftar keanggotaan yang rapi secara protokoler.
Seluruh drama audiensi itu semakin memperlihatkan bagaimana ruang partisipasi publik kerap diatur melalui kacamata etik yang timpang. Kehadiran seorang tersangka dianggap tidak patut, tetapi menghadirkan seorang kapolri yang sedang dipersoalkan secara nasional justru dianggap sah. Etika yang seharusnya menjadi pagar moral, dioperasikan secara selektif, mengikuti arus kepentingan politik yang lebih besar. Di sinilah publik melihat bahwa ketidaksinkronan antara ucapan dan tindakan bukan lagi anomali, melainkan praktik yang kian dianggap lumrah.
Dalam berbagai studi internasional, seperti yang dipaparkan UNODC dan International Crisis Group, negara-negara yang berhasil merombak institusi kepolisian menjadikan keberanian mendengarkan suara korban sebagai titik tolak reformasi. Georgia di era Mikheil Saakashvili atau Afrika Selatan pasca apartheid menempatkan partisipasi publik sebagai pilar utama. Reformasi yang dimulai tanpa mengakomodasi keluhan masyarakat hanya akan melahirkan perubahan kosmetik, bukan transformasi struktural. Indonesia tampaknya belum memilih jalan itu.
Keputusan Presiden Prabowo, pada akhirnya, menjadi cermin dari arah politik negara dalam menata institusi keamanan. Ketika publik menuntut polisi yang lebih transparan, profesional, dan bebas dari tekanan politik, keputusan merekrut figur kontroversial ke dalam badan reformasi justru memperlemah kepercayaan publik terhadap kesungguhan negara. Jargon reformasi terdengar nyaring, tetapi langkah-langkah yang diambil tidak berjalan pada rel akal sehat.
Dalam suasana seperti ini, harapan masyarakat untuk memiliki polisi yang melindungi dan mengayomi mungkin terasa semakin jauh. Namun sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa ketika ruang formal untuk menyampaikan aspirasi digerogoti, publik selalu mencari cara untuk didengar. Kesabaran rakyat adalah berkah sekaligus peringatan. Reformasi tidak akan bergerak bila terus dipeluk oleh figur yang sedang dipersoalkan, dan demokrasi tidak akan sehat bila akal sehat terus dikalahkan oleh kenyamanan politik. Jika republik ini ingin kembali pada relnya, reformasi Polri harus dimulai dari keberanian moral yakni keberanian untuk mendengar, bukan menyingkirkan; keberanian untuk membenahi, bukan menutupi; dan keberanian untuk menempatkan akal sehat di atas semua kalkulasi kekuasaan.
(Samsul Daeng Pasomba.PPWI/Tim)