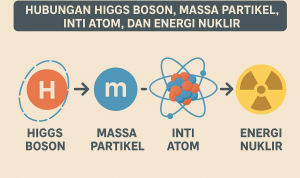Oleh: Muhammad Asdar, Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI Cabang Bulukumba
Mabesnews.com.Bulukumba – Ironis, ketika para intelektual justru menjadi pemutus mata rantai dari akar intelektual itu sendiri. Di tengah derasnya arus informasi dan gelombang modernisasi, kita justru menyaksikan kemunduran cara berpikir kritis, hilangnya daya refleksi, dan tercerabutnya warisan intelektual dari akarnya yang paling mendalam. Ini bukan soal kurangnya pengetahuan, melainkan kegagalan memaknainya.
Hari ini, gelar akademik dan akses terhadap ilmu tidak otomatis melahirkan kejernihan berpikir atau keberanian moral. Intelektual lebih sering tampil sebagai simbol prestise, bukan sebagai agen perubahan. Kita sibuk mengutip, namun enggan mempertanyakan. Mahir menguraikan, namun lupa mendalami makna. Inilah luka sunyi dalam gelapnya dunia pemikiran kita: ketika warisan intelektual yang seharusnya membumi dan membebaskan, justru dimatikan oleh tangan-tangan yang mengaku mewarisinya.
Pertanyaannya bukan lagi sekedar “mengapa”, tetapi “untuk siapa” dan “demi apa” pengetahuan itu dirawat? Jika intelektualitas hanya berakhir di menara gading tanpa keberpihakan pada realitas sosial, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan kematian akar intelektual—di tangan mereka yang semestinya menjaganya tetap hidup dan tumbuh.
Kita belajar dari para tokoh seperti Soedjatmoko, Tan Malaka, Abdurrahman Wahid, Pramoedya Ananta Toer, Ahmad Dahlan, Cak Nur, hingga Franz Magnis-Suseno. Mereka tidak sekedar menguasai teori, tetapi menyelam dalam denyut kehidupan rakyat. Mereka memahami luka kolektif dan merumuskannya menjadi kesadaran kritis. Hari ini, banyak intelektual justru menjauh dari ruang sosial—tenggelam dalam seminar, sibuk di ruang kopi, namun kehilangan kemampuan untuk merasakan dan memahami.
Pengasingan diri yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Søren Kierkegaard, Imam Al-Ghazali, Tan Malaka, hingga Pramoedya Ananta Toer bukanlah tanpa alasan. Mereka menolak tunduk pada sistem akademik yang mengukur keberhasilan berdasarkan kuantitas publikasi, bukan kualitas pemikiran. Maka, yang lahir adalah intelektual teknokrat: cakap mengolah data, lihai menyusun retorika, namun kering makna dan kehilangan arah moral.
Ke depan, saya berharap generasi muda—terutama mahasiswa—tidak menjadikan pengetahuan semata-mata sebagai akumulasi informasi, melainkan sebagai perenungan etis di tengah derasnya problematika sosial. Sebab, ketika ilmu diproduksi tanpa kompas moral, yang lahir adalah pengetahuan tanpa orientasi.
Di Kabupaten Bulukumba, akar intelektual lahir dari pergulatan sejarah, budaya, dan nilai-nilai lokal. Di sinilah ilmu semestinya berpijak—pada perjuangan kelas sosial yang diridai Tuhan. Kita bukanlah pemuda dengan narasi dominan yang siap disewakan. Kita adalah penjaga akar intelektual, dan keberpihakan kita adalah pada realitas, bukan pada gelar dan pengakuan semu.*