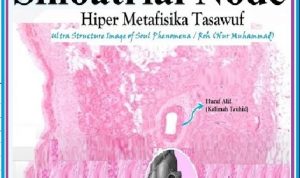Mabesnews.com,Jakarta – Dalam pusaran kasus Hogi di Sleman, publik kembali diguncang oleh pernyataan tajam yang dikemukakan Wilson Lalengke. Ia menyoroti fenomena gelar akademik yang disandang oleh sejumlah anggota Polri, khususnya gelar S.H. (Sarjana Hukum) dan M.H. (Magister Hukum).
Menurutnya, gelar tersebut tidak mencerminkan kompetensi hukum, melainkan sekadar pajangan yang justru menimbulkan bahan tertawaan rakyat. “Gelar S.H. dan M.H. bagi kebanyakan anggota Polri bukanlah singkatan Sarjana Hukum atau Magister Hukum, tapi Sarjana Humor dan Magister Humor,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dengan nada getir, Jumat, 30 Januari 2026.
Lawakan tak lucu dan pahit itu muncul setelah terbongkar kasus kriminalisasi Hogi Minaya yang dijadikan pesakitan oleh “kedunguan” oknum Kapolres Sleman, Kombes Pol. Edy Setyanto Erning Wibowo, S.I.K., M.H. “Seorang anggota polisi bergelar Sarjana Ilmu Kepolisian dan Magister Hukum, tapi tidak paham KUHAP dan KUHP, ini aneh sekali,” kata para legislator DPR RI setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan sang Kapolres Sleman di Gedung Senayan Jakarta baru-baru ini.
Pernyataan Wilson Lalenke soal Sarjana Humor dan Magister Humor di atas itu bukan sekadar kritik terhadap individu, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang integritas, kualitas pendidikan, dan tanggung jawab moral aparat penegak hukum. Kasus Hogi di Sleman menjadi cermin betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika aparat yang seharusnya memahami KUHAP dan KUHP justru menunjukkan ketidakmampuan mendasar dalam menerapkannya.
*Gelar sebagai Simbol atau Substansi?*
Di masyarakat kita, gelar akademik sering dipandang sebagai simbol status sosial. Ia menjadi semacam “mahkota” yang dipajang di kartu nama, papan nama, atau bahkan di seragam resmi. Namun, pertanyaan filosofis yang patut diajukan adalah apakah gelar akademik benar-benar mencerminkan kualitas intelektual dan moral seseorang? Apakah gelar itu sekadar simbol kosong, ataukah ia harus menjadi bukti nyata dari penguasaan ilmu dan tanggung jawab etis?
Dalam konteks aparat penegak hukum, gelar S.H. dan M.H. seharusnya menandakan penguasaan mendalam atas hukum pidana, hukum acara, serta prinsip-prinsip keadilan. Tetapi jika gelar itu diperoleh dari universitas abal-abal, atau sekadar formalitas tanpa substansi, maka ia tidak lebih dari topeng akademik. Topeng yang menutupi kekosongan intelektual, dan pada akhirnya mempermalukan institusi serta mencederai kepercayaan rakyat.
Kasus Hogi di Sleman menjadi titik terang atas kritik Wilson Lalengke. Publik menyaksikan bagaimana aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru tampak gagap dalam memahami aturan dasar. Ketidakmampuan ini bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan indikasi adanya masalah sistemik: kualitas pendidikan hukum yang rendah, praktik jual-beli ijazah, dan budaya birokrasi yang lebih mementingkan simbol daripada substansi.
Pertanyaan filosofis lainnya yang muncul kemudian adalah bagaimana mungkin keadilan ditegakkan oleh mereka yang tidak memahami hukum? Dan, apakah negara bisa disebut beradab jika aparatnya lebih sibuk memamerkan gelar daripada menegakkan kebenaran?
Kasus Hogi bukan hanya tragedi individu, melainkan tragedi sistem. Ia menunjukkan bahwa ketika integritas akademik runtuh, maka integritas hukum pun ikut runtuh. Dan ketika hukum runtuh, masyarakat kehilangan pegangan moral.
*Nasihat untuk Aparat dan Akademisi*
Wilson Lalengke memberikan saran keras: jangan gunakan gelar S.H. dan M.H. jika tidak memahami substansinya. Saran ini, meski terdengar sinis, sesungguhnya adalah panggilan moral. Gelar bukanlah hiasan, melainkan tanggung jawab.
Bagi aparat Polri, katanya, jangan jadikan gelar sebagai tameng atau pajangan. Jadikan ia sebagai komitmen untuk memahami hukum secara mendalam dan menegakkannya dengan jujur. Bagi universitas agar jangan menjual ijazah sebagai komoditas. Pendidikan adalah amanah, bukan bisnis. Universitas abal-abal yang melahirkan lulusan tanpa kompetensi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Dan, bagi masyarakat supaya jangan terpesona oleh gelar. Nilailah seseorang dari integritas, kompetensi, dan moralitasnya.
Dalam filsafat, gelar akademik dapat dipandang sebagai simbol logos (akal budi) yang seharusnya membimbing tindakan. Namun, ketika gelar kehilangan substansi, ia berubah menjadi simulacra atau sekadar bayangan tanpa realitas. Jean Baudrillard (filsuf Prancis, 1929-2007) mengingatkan bahwa masyarakat modern sering terjebak dalam dunia simulasi, di mana tanda-tanda kehilangan makna aslinya.
Kini, pertanyaan reflektif yang patut direnungkan adalah apakah kita sedang hidup dalam masyarakat simulasi, di mana gelar hukum tidak lagi berarti penguasaan hukum, melainkan sekadar tanda kosong? Atau, apakah keadilan bisa ditegakkan jika simbol-simbol akademik telah kehilangan makna?
Jika jawabannya adalah “tidak,” maka tugas kita adalah mengembalikan makna gelar kepada substansinya. Gelar harus kembali menjadi bukti nyata dari penguasaan ilmu dan komitmen moral, bukan sekadar pajangan.
*Kisah Hogi sebagai Momentum Perubahan*
Kasus Hogi di Sleman seharusnya menjadi momentum untuk mereformasi sistem pendidikan hukum dan institusi penegak hukum. Kita tidak boleh membiarkan tragedi ini berlalu begitu saja. Ia harus menjadi pelajaran kolektif bahwa integritas akademik dan integritas hukum adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.
Kebenaran tidak bisa ditegakkan oleh kebohongan. Jika gelar diperoleh dengan cara curang, maka hukum yang ditegakkan pun akan rapuh. Keadilan membutuhkan pengetahuan. Tanpa pemahaman mendalam atas hukum, keadilan hanya menjadi slogan kosong.
“Harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa integritas adalah fondasi seluruh bidang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Gelar tanpa integritas adalah kehampaan, dan kehampaan tidak bisa menjadi dasar bagi negara hukum,” terang lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University (England) dan bidang Applied Ethics dari Utrecht University (The Netherlands) serta Linkoping University (Sweden) itu.
Wilson Lalengke menutup pernyataannya dengan kata “MEMALUKAN..!!!” Kata ini menggema sebagai tamparan keras bagi aparat, universitas, dan masyarakat. Namun, di balik rasa malu, ada peluang untuk berubah, memperbaiki diri.
Sekarang, apakah kita akan terus membiarkan gelar menjadi bahan tertawaan rakyat, ataukah kita akan menjadikannya sebagai simbol integritas dan keadilan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah bangsa. Jika kita memilih integritas, maka kasus Hogi akan dikenang sebagai titik balik. Tetapi jika kita memilih simbol kosong, maka ia akan menjadi catatan kelam dalam sejarah hukum Indonesia.
“Nasehat kepada kita semua, jangan pernah menjadikan gelar sebagai pajangan. Jadikan ia sebagai komitmen hidup untuk menegakkan kebenaran, membela keadilan, dan menjaga martabat bangsa. Karena pada akhirnya, bukan gelar yang akan diingat rakyat, melainkan integritas dan keberanian kita dalam menegakkan hukum secara benar demi menghadirkan keadilan di tengah masyarakat,” pesan Wilson Lalengke menutup pernyataannya.
Hombing